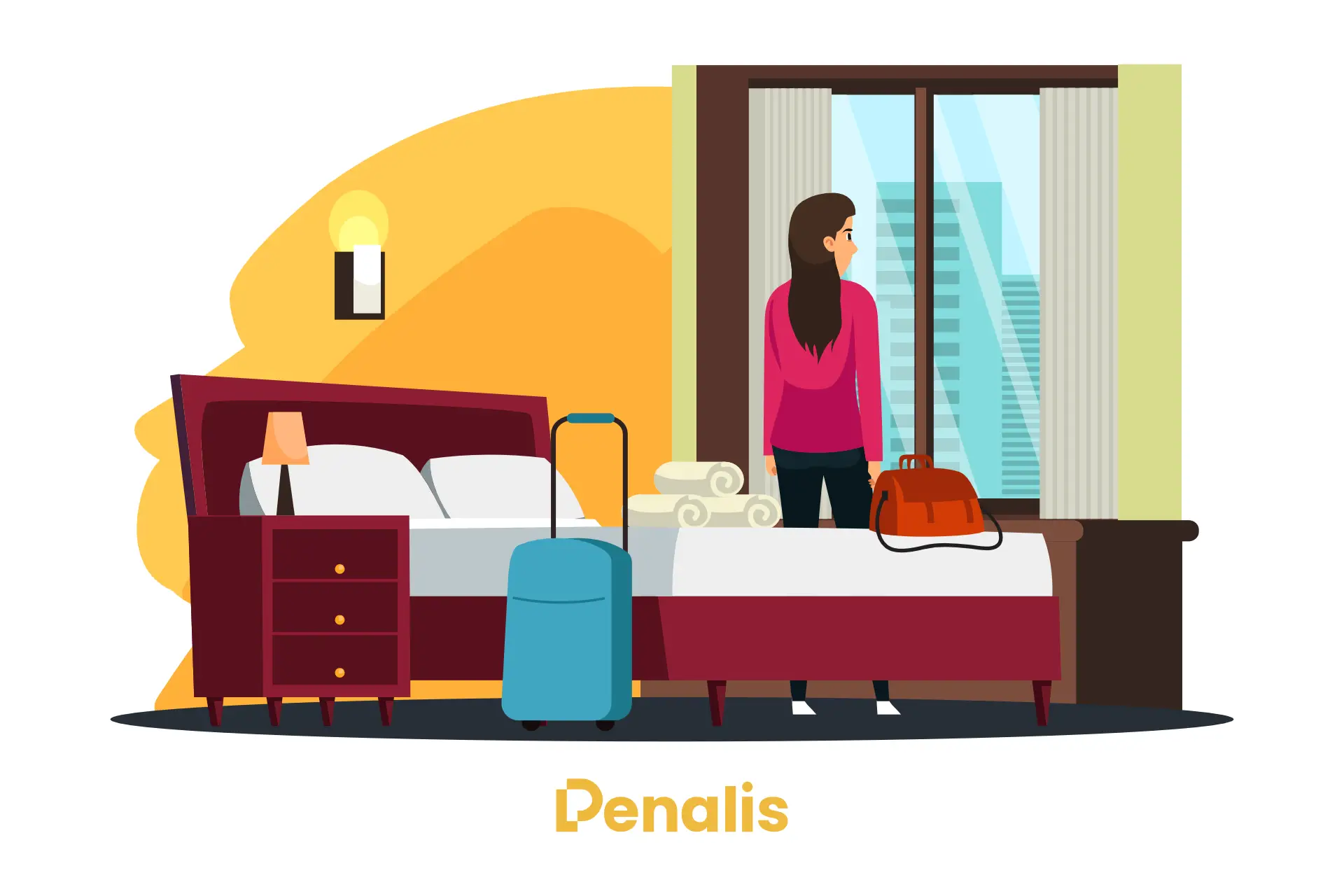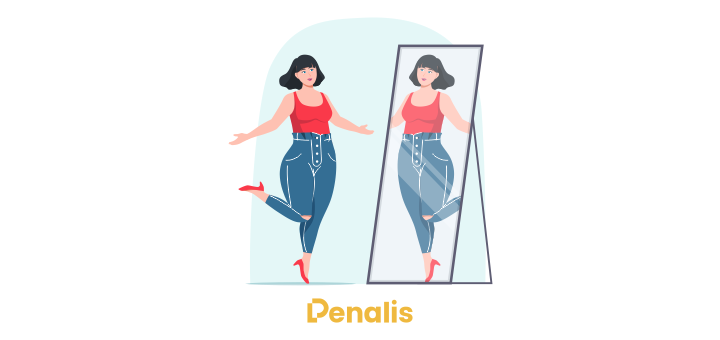Turun dari LRT di Cawang, saya sempat merasa seperti warga ibu kota yang modern. Langkah kaki terasa ringan, jalur pedestrian mulus dan suasana stasiun yang kinclong membuat saya percaya Jakarta memang sedang berubah. Tapi optimisme itu langsung rontok begitu saya coba menyambung perjalanan ke Terminal Kampung Rambutan.
Saya disambut jalanan berdebu, semak liar, suara klakson yang membelah langit dan trotoar yang (…..) ya, sebenarnya gak bisa dibilang trotoar juga sih, karena lebih mirip sisa urukan proyek yang lupa diberesin. Di sinilah, katanya, titik integrasi transportasi berada. Bus antarkota, Transjakarta, LRT, semua ketemu di Kampung Rambutan. Sayangnya, yang belum ketemu itu adalah niat buat membenahi lingkungan sekitarnya.
Sebagai terminal besar yang katanya jadi simpul mobilitas Jakarta dan daerah sekitarnya, Kampung Rambutan sebenarnya punya potensi. Ada area Transjakarta, angkot, bus AKAP, sampai akses menuju LRT. Tapi untuk berpindah dari satu moda ke moda lain, kita harus siap jadi atlet dadakan: lari-lari kecil hindari motor nyelonong, lompatin genangan air dan sesekali main tebak-tebakan jalan mana yang aman dilewati. Gak heran kalau banyak warga bilang: “Kalau mau naik LRT dari Rambutan, mental harus kuat. Bukan cuma tiket yang siap, tapi juga fisik”.
Saya sempat ketemu seorang ibu yang baru turun dari bus antarkota. Tujuannya sederhana: mau lanjut naik Transjakarta ke daerah Matraman. Tapi jalannya becek, enggak ada petunjuk arah yang jelas dan yang paling nyebelin, dia harus jalan kaki sejauh hampir 500 meter dengan bawaan segambreng. “Ini katanya Jakarta makin terintegrasi. Tapi kenapa rasanya saya makin terisolasi?” katanya sambil ketawa miris.
Ironinya, Jakarta punya rencana besar soal transportasi publik. Dengar-dengar, targetnya bikin warga cinta naik kendaraan umum dan ninggalin kendaraan pribadi. Tapi sayangnya, cinta itu nggak cukup modal armada. Harus juga ada kenyamanan, kejelasan, dan keamanan. Dan Terminal Kampung Rambutan, dalam banyak hal, masih jadi contoh bagaimana pembangunan infrastruktur kadang cuma fokus ke gedung dan halte, tapi lupa bahwa manusia yang lewat juga butuh jalan kaki yang layak.
Kadang saya mikir, mungkin yang benar-benar terintegrasi itu bukan transportasinya, tapi rasa sabar warga Jakarta.
Saya jadi ingat waktu naik Transjakarta dari arah Ragunan. Turun di halte Kampung Rambutan, saya coba cari jalan ke arah LRT. Dan seperti deja vu, saya harus jalan kaki ngelewatin semacam gang kecil yang entah kenapa dijadikan akses pejalan kaki resmi. Jalan sempit, berkelok, ngelewatin parkiran liar dan pas di ujung jalan, saya disambut tangga setinggi harapan yang belum kesampaian.
Padahal di brosur dan infografis dinas perhubungan, semuanya kelihatan mulus. Halte ke stasiun? Terhubung. LRT ke Transjakarta? Terintegrasi. Terminal ke kehidupan yang lebih baik? Terjangkau. Tapi di lapangan, rasa-rasanya yang terhubung cuma rasa bingung.
Saya tahu, perubahan itu nggak bisa instan. Tapi masalahnya, banyak hal yang bukan butuh revolusi besar,cuma perbaikan kecil yang masuk akal. Misalnya, pasang papan petunjuk arah. Perbaiki jalur pedestrian. Tambahkan lampu jalan. Hal-hal kecil yang bikin warga merasa diperhatikan. Karena seringkali bukan infrastruktur megah yang bikin orang nyaman, tapi kepedulian kecil yang konsisten.
Dan lucunya, saya bukan orang yang anti dengan perkembangan. Saya senang ada LRT. Saya dukung Transjakarta makin luas jaringannya. Tapi kalau akses menuju semuanya itu masih kayak uji nyali, ya jangan heran kalau orang lebih milih naik motor atau mobil pribadi.
Akhirnya saya paham, di Jakarta ini yang paling kuat itu bukan armada bus, bukan rel LRT, bukan kabel optik. Tapi tekad warga buat terus bertahan di tengah tata kota yang kadang lupa kalau manusianya juga butuh ruang buat sekadar melangkah.
Jadi, kalau boleh nitip pesan buat Dinas Perhubungan: “Transportasi publik itu bukan cuma soal armada dan halte. Tapi juga soal rute kecil yang kadang tidak terlihat di Google Maps, jalur kaki warga biasa yang berharap bisa sampai tujuan tanpa harus jatuh dulu ke got”.